Budaya Bukan Sekadar Warisan, Tapi Energi Masa Depan

Dr. Yunada Arpan (Dosen STIE Gentiaras Lampung)
“Di tengah arus globalisasi, kebudayaan Indonesia perlu dipandang bukan hanya sebagai peninggalan masa lalu, tetapi sebagai kekuatan ekonomi, sosial, dan diplomasi bangsa”
RadarCyberNusantara.id | Menteri Kebudayaan RI pada 7 Juli 2025 lalu menerbitkan Surat Keputusan No. 162/M/2025. Penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional menandai pengakuan negara terhadap peran strategis kebudayaan dalam membentuk identitas bangsa. Namun, kebudayaan tidak boleh berhenti diperlakukan sebagai simbol atau seremoni tahunan. Ia harus dikelola sebagai kekuatan ekonomi kreatif, sosial, dan diplomasi yang mampu bersaing di tengah arus globalisasi. Hanya dengan cara itu, budaya Indonesia benar-benar menjadi energi masa depan, bukan sekadar warisan masa lalu.
Alasan yang dikemukakan pemerintah berlapis: sebagai pengakuan negara atas peran strategis kebudayaan, upaya memperkuat identitas bangsa di tengah arus globalisasi, serta merujuk pada sejarah 17 Oktober 1951 saat Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan melalui PP No. 66. Penetapan ini diharapkan menjadi momentum untuk menempatkan kebudayaan tidak hanya sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai energi masa depan. Namun pertanyaannya, apakah langkah simbolik ini akan benar-benar bertransformasi menjadi gerakan kultural yang nyata?
Kebudayaan adalah fondasi yang membentuk identitas bangsa. Tanpa kebudayaan, Indonesia hanyalah kumpulan administratif dari ribuan pulau yang berbeda. Justru melalui kebudayaan—bahasa, seni, tradisi, nilai-nilai—bangsa ini menemukan benang merah persatuan. Dalam konteks global, kebudayaan juga menjadi wajah yang memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Seperti halnya Korea Selatan dengan Hallyu Wave atau Jepang dengan anime, Indonesia sebenarnya memiliki modal budaya yang tak kalah kuat: batik, wayang, gamelan, keris, hingga kuliner Nusantara yang telah diakui UNESCO.
Namun, identitas itu seringkali hanya dirayakan secara seremonial. Peringatan hari-hari besar budaya kadang berhenti pada parade, pertunjukan, atau slogan tanpa strategi berkelanjutan. Di sinilah tantangan sekaligus kritik terhadap penetapan Hari Kebudayaan Nasional. Jangan sampai tanggal 17 Oktober hanya sekadar “hari foto bersama,” sementara persoalan mendasar pelestarian budaya dibiarkan berjalan seadanya.
Arus globalisasi membawa dua wajah. Di satu sisi, ia membuka ruang bagi budaya Indonesia untuk dikenal dunia melalui media digital. Di sisi lain, ia juga mengancam homogenisasi. Anak muda lebih fasih menyanyikan lagu pop asing ketimbang tembang daerah; lebih mengenal makanan cepat saji daripada kuliner tradisional. Ironisnya, budaya lokal sering dianggap kuno, padahal justru menyimpan kearifan ekologis, sosial, dan spiritual yang relevan hingga kini.
Komersialisasi budaya juga menimbulkan dilema. Batik misalnya, sering direduksi sekadar motif fesyen tanpa pemahaman tentang filosofi dan sejarahnya. Begitu pula pertunjukan adat yang diubah demi kepentingan pariwisata massal. Budaya yang semula hidup dalam konteks komunitas, lambat laun terancam kehilangan ruhnya.
Meski tantangannya nyata, peluang yang dimiliki Indonesia jauh lebih besar. Pengakuan UNESCO terhadap berbagai warisan budaya Indonesia adalah bukti bahwa dunia memberi tempat terhormat bagi kita. Tinggal bagaimana bangsa ini mengelola potensi tersebut secara serius.
Budaya bisa menjadi basis ekonomi kreatif yang menyejahterakan rakyat. Industri musik, film, kuliner, hingga kerajinan tradisional memiliki nilai pasar global yang menjanjikan. Generasi muda juga mulai mengambil peran penting melalui media sosial, konten digital, hingga start-up berbasis budaya. Mereka membuktikan bahwa budaya tidak harus dipelihara secara statis, melainkan bisa dikreasikan ulang sesuai zaman tanpa kehilangan akar.
Hari Kebudayaan Nasional seharusnya bukan hanya seremoni tahunan. Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan berkelanjutan: dukungan dana bagi komunitas budaya di daerah, perlindungan hak cipta warisan tradisi, revitalisasi bahasa daerah, serta penguatan pendidikan budaya di sekolah. Selain itu, kolaborasi lintas sektor mutlak diperlukan. Dunia akademik, seniman, industri kreatif, hingga masyarakat lokal harus dilibatkan dalam perumusan arah kebijakan budaya.
Tidak kalah penting, partisipasi publik harus diperluas. Penetapan hari budaya yang dilakukan melalui keputusan menteri memang simbol penting, tetapi legitimasi sejatinya datang dari keterlibatan masyarakat luas. Budaya tidak bisa ditentukan hanya lewat dokumen resmi, melainkan harus hidup dalam praktik sehari-hari: dari cara kita berpakaian, berinteraksi, hingga mengelola lingkungan.
Tanggal 17 Oktober kini akan dikenang sebagai Hari Kebudayaan Nasional. Tetapi hari ini tidak boleh berhenti sebagai tanda di kalender. Ia harus menjadi momentum lahirnya kesadaran baru bahwa kebudayaan adalah investasi jangka panjang bangsa. Sejarah menunjukkan, bangsa yang besar bukan hanya kuat dalam ekonomi dan militer, melainkan juga kaya dalam kebudayaan.
Kebudayaanlah yang menjadi daya tahan dan daya tawar Indonesia di kancah global. Maka, Hari Kebudayaan Nasional harus kita maknai sebagai ajakan kolektif: menjaga, menghidupkan, sekaligus mengembangkan budaya Nusantara agar tetap relevan dan berdaya saing. Karena pada akhirnya, kebudayaan bukan hanya soal masa lalu yang kita kenang, tetapi juga tentang masa depan yang kita bangun bersama.
|Red
































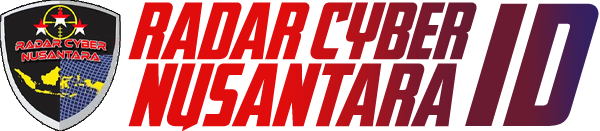
Tidak ada komentar